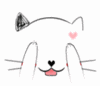Kekuasaan jelas menggoda. Dalam konteks politik,
Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan cenderung dilanggengkan oleh setiap
penguasa lewat berbagai cara. Cara apapun tidak menjadi persoalan, yang penting
kekuasaan itu dapat dipertahankan. Dari pandangan Machiavelli ini tersirat
diterimanya cara-cara kekerasan dan represi (coercion, violence) yang
tidak etis dalam mempertahankan kekuasaan. John Locke di Inggris, Montesqiueu
di Prancis, dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat juga beranggapan bahwa
penguasa cenderung memiliki ambisi untuk berkuasa terus-menerus. Karenanya,
kepentingan penguasa sering bertolak belakang dengan kepentingan rakyat banyak.
Dalam
banyak sistem sosial dan politik kekuasaan memang dicoba-batasi agar tidak
menjadi absolut atau totaliter, termasuk dalam pandangan Machiavelli yang
menghendaki Italia menjadi negara republik. Ada banyak cara diusulkan untuk
membatasi kekuasaan. Para filosof, ahli hikmah dan etika mengajarkan agar
kekuasaan dipegang oleh figur filosof dan tokoh bermoral (ulama, cendekiawan).
Kekuasaan berada di bawah hukum, bukan lagi “Aku [baca: raja] adalah hukum”.
Dari sisi struktur dan sistem, pemikir-pemikir politik lalu menganjurkan agar
kekuasaan dibagi (separation of power) antara lembaga-lembaga negara;
otoritas dibelah (distribution of power), seperti pada ajaran trias
politica.
Dalam sistem politik totaliter, kekuasaan menjadi
absolut, terpusat pada segelintir elite (oligarkhi) yang berlaku zalim, dan
tidak mengenal partisipasi publik dalam kehidupan politik, baik yang
konvensional (seperti: memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik,
membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok kepentingan) maupun yang non-konvensional
(seperti unjuk rasa). Padahal partisipasi ini mengingatkan pada pentingnya
jaminan akan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi (civil rights),
seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan penghormatan terhadap hak
asasi warga negara. Civil rights adalah salah satu dari dua kaki
demokrasi, sedang kaki yang satunya lagi adalah parlementarisme, yang terkait
dengan keharusan adanya parlemen, partai politik, dan pemilihan umum.
Demokrasi,
menurut Bertrand Russel, mengandung kelemahan, terutama menyangkut dua hal:
keputusan yang harus cepat diambil dan menyangkut kemampuan atau pengetahuan
seorang pengambil kebijakan. Pada tingkat ini biasanya terjadi penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power), dimana kewenangan yang dimiliki pejabat
publik bukan digunakan untuk kemaslahatan publik, tetapi untuk kepentingan
pribadi sang pejabat. Mengingat besarnya kekuatan godaan dan tarikan kekuasaan
terhadap para penguasa, Lord Acton membuat suatu tesis aksiomatik yang sangat
terkenal: “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.”
Sayangnya,
menurut saya, sebagai sistem, demokrasi kekurangan alat (tool) untuk
mengontrol penyalahgunaan kekuasaan, selain dengan jaminan partisipasi publik
dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang antara lain dicerminkan dengan
pengawasan masyarakat dan parlemen atas kinerja pemerintah, serta penggunaan
hukum sebagai sistem pemberi sanksi atas ilegalitas kekuasaan. Karena itu,
moralitas dan akhlak agama mempunyai peran signifikan, sebagaimana dilihat para
filosof da ahli hikmah di atas.
PEYIMPANGAN DEMOKRASI ORDE LAMA
Kaburnya
sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik
Peranan parlemen
yang lemah
Jaminan hak-hak
dasar warga negara masih lemah
Terjadinya
sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah
Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak
media masa yang tidak dijinkan terbit
Akhirnya
dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G 30 S / PKI pada
tanggal 30 September 1965. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan
presiden Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada
yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. PKI ingin membentuk angkatan
kelima sedangkan militer tidak menyetujuinya. Akhir dari demokrasi terpimpin
ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden
Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.
Pada
era orde lama (1955-1961), situasi negara Indonesia diwarnai oleh berbagai
macam kemelut ditngkat elit pemerintahan sendiri. Situasi kacau (chaos) dan persaingan
diantara elit politik dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembenuhan 6
jenderal pada 1 Oktober 1965 yang kemudian diikuti dengan dengan krisi politik
dan kekacauan sosial. Pada massa ini persoalan hak asasi manusia tidak
memperoleh perhatian berarti, bahkan cenderung semakin jauh dari harapan.
PEYIMPANGAN DEMOKRASI REFORMASI
Refleksi 15 Tahun Reformasi
Kegagalan perjalanan 15 tahun reformasi dalam mewujudkan perubahan yang nyata dan substansial bagi rakyat sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari deviasi partai politik. Dalam konteks ini, partai politik lah yang sesungguhnya sebagai entitas politik yang bertanggungjawab atas terhambatnya perubahan rakyat, mengingat partai politik sejatinya merupakan instrument politik yang memiliki posisi dan peran penting dalam demokrasi. Partai politik adalah pilar dan sekaligus basis demokrasi. Demokrasi yang berlangsung baik sangat bergantung pada sejauhmana sistem kepartaian berfungsi dengan baik di dalamnya.
Partai-partai politik faktanya tidak menunjukkan peran-peran yang dibutuhkan oleh rakyat. Partai politik selama ini cenderung banyak berkutat dengan urusan pertarungan politik kekuasaan dan jabatan, daripada memerankan diri sebagai instrumen agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat. Fungs-fungsi sebagai alat penekan atau pengawasan pemerintah melalui anggotanya di parlemen juga tidak maksimal. Sementara itu, para pemimpin pemerintahan yang berasal dari partai politik gagal di dalam membangun politik yang otentik yakni politik yang memajukan dan membahagiakan rakyat.
Kegagalan partai politik untuk berperan dengan baik ini terjadi sebagai akibat dari berbagai deviasi atau penyimpangan fungsi dan tujuan partai. Hal itu banyak ditunjukkan oleh praktek politik elit dan anggota partai politik khususnya yang menduduki jabatan-jabatan politis baik di dalam partai atau struktur kenegaraan. Partai politik pada kenyatannya cenderung menjadi alat politik kekuasaan semata, instrument eksploitasi berbagai sumber daya.
Ketidaan ideologi yang jelas adalah faktor terbesar mengapa terjadi deviasi fungsi dan peran partai-partai politik di Indonesia. Ideologi adalan seperangkat nilai yang penting yang berfungsi menjadi basis dari tujuan dan perjuangan politik suatu partai. Problem ideologi ini dalam realitasnya membuat partai politik menjadi rentan terhadap penetrasi berbagai kepentingan privat yang menungganginya. Tujuan dan perjuangan politiknya menjadi tidak jelas. Tidak ada kerangka kerja programatik untuk ditawarkan kepada rakyat.
Ketidakjelasan kaderisasi dan proses rekruitmen kandidat calon wakil rakyat yang lebih memperhatikan modal ekonomi, bukan karena pertimbangan kapasitas, komitmen atas demokrasi, hak asasi, dan perjuangan mewujudkan agenda kerakyatan.
Lebih lanjut, deviasi fungsi-fungsi partai politik ini melahirkan berbagai persoalan. Dalam politik misalnya, politik berubah hanya menjadi arena terbatas bagi elit politik dan bersamaan dengan itu meminggirkan rakyat. Politik dengan demikian hanya menjadi arena bagi yang memiliki modal ekonomi. Politik yang sejatinya arena mewujudkan kehidupan dan kebaikan bersama menjadi terdistorsi. Politik menjadi arena perebutan kekuasaan dan jabatan di DPR atau kabinet. Rakyat tidak lagi dianggap penting kecuali sebagai target perolehan suara untuk kepentingan memenangi pemilu atau Pilkada.
Dalam kebijakan implikasinya bisa dilihat dengan munculnya regulasi-regulasi yang bermasalah. Banyak UU yang dihasilkan parlemen menabrak Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi. Fakta ini bisa dilihat dari banyaknya UU yang diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap inkonstitusional.
Kemunculan berbagai regulasi politik yang bermasalah ini tidak dilepaskan dari masuknya logika politik transaksional dalam pembahasan regulasi di parlemen. UU sebagai hasilnya sarat dengan kepentingan. Persoalan ini misalnya juga dinyalir oleh Mahfud MD, mantan Ketua MK, bahwa selain persoalan profesionalisme dari para pembuat undang-undang, menurutnya juga ada dugaan berbagai kepentingan dengan tukar-menukar kepentingan politik dalam pembentukan UU. Padahal sebagai representasi rakyat, mereka harus mengaggregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat dalam kebijakan, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan.
Banyak UU selain yang secara normative tidak hanya inkonstitusional, melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi secara praktek akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Beberapa regulasi di sektor keamanan bermasalah, misalnya UU Penanganan Konflik Sosial, RUU Kamnas, RUU Ormas, dan lain-lain.
Sementara itu, banyak kasus korupsi dan suap yang melibatkan orang-orang partai politik juga adalah cerminan dari deviasi partai politik. Persoalan ini kenyataannya tidak hanya terjadi di pusat, melainkan juga banyak di daerah. Banyak orang-orang partai politik khususnya yang menduduki jabatan publik diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi dan suap yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana beberapa di antaranya ada yang divonis kurungan penjara.